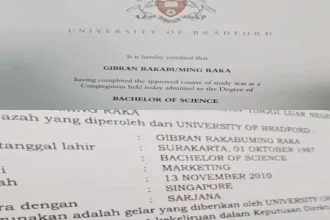Selama ini di Indonesia, istilah “kerugian negara” selalu identik dengan korupsi. Begitu ada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut “terdapat kerugian negara”, publik langsung berpikir: ada yang korup!
Namun, di banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, atau Jerman, konsep ini tidak serta-merta dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
Mengapa bisa begitu? Apa bedanya sistem hukum mereka dengan kita? Dan apakah artinya Indonesia terlalu luas menafsirkan korupsi?
Mari kita bahas pelan-pelan.
⚖️ Korupsi di Mata Dunia: Bukan Sekadar Uang Hilang
Bagi banyak negara maju, korupsi bukan hanya soal uang, tapi tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
Definisi yang banyak diadopsi berasal dari Transparency International, yaitu:
“Abuse of entrusted power for private gain”
(Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk memperoleh keuntungan pribadi).
Artinya, kerugian keuangan negara hanyalah dampak, bukan unsur utama dari korupsi.
Contoh sederhana:
Seorang pejabat publik menerima suap untuk memenangkan tender proyek. Itu korupsi, meskipun belum tentu langsung ada angka pasti tentang kerugian negara.
Sebaliknya, kalau pejabat mengambil keputusan salah yang mengakibatkan proyek gagal dan merugi, belum tentu korupsi, selama tidak ada niat jahat atau keuntungan pribadi.
🇮🇩 Di Indonesia: “Kerugian Negara” Jadi Indikator Hukum
Berbeda dengan negara maju, di Indonesia UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) — khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 — menjadikan “merugikan keuangan negara” sebagai unsur utama.
Artinya, begitu ada kerugian negara, penyidik dan jaksa bisa menjerat seseorang meskipun tidak ditemukan uang suap, gratifikasi, atau transfer ilegal.
Akibatnya, banyak kasus yang sebenarnya bersifat administratif atau kesalahan kebijakan, justru masuk ranah pidana korupsi.
Padahal, dalam banyak praktik di dunia, hal seperti ini biasanya diselesaikan secara administratif, etika, atau perdata, bukan pidana.
🏛️ Mengapa Negara Maju Tak Gunakan Konsep Ini?
Ada beberapa alasan mengapa negara-negara dengan sistem hukum matang tidak menjadikan “kerugian negara” sebagai dasar korupsi:
1. 🔍 Fokus pada Niat Jahat (Mens Rea)
Dalam sistem hukum Anglo-Saxon maupun civil law modern, pidana selalu menuntut unsur kesengajaan atau niat jahat.
Kalau kerugian muncul karena salah hitung, kebijakan gagal, atau force majeure, itu dianggap risiko pemerintahan, bukan kejahatan.
Sementara di Indonesia, aparat sering berangkat dari hasil audit BPK: “ada kerugian negara” → langsung masuk tahap penyidikan.
Padahal belum tentu ada unsur niat jahat.
2. 🧾 Kerugian Negara Bisa Dikembalikan
Dalam hukum administrasi keuangan di negara maju, kalau ada kesalahan pengelolaan dana publik, solusinya adalah pengembalian atau koreksi administratif, bukan hukuman pidana.
Contohnya di Inggris, pejabat bisa diminta mengembalikan dana yang salah pakai. Tapi selama tidak terbukti memperkaya diri, itu bukan korupsi.
Pendekatan ini mendorong pembelajaran kebijakan, bukan ketakutan membuat keputusan.
3. 📈 Manajemen Risiko di Pemerintahan
Pemerintahan modern mengakui bahwa setiap kebijakan publik mengandung risiko — termasuk risiko keuangan.
Proyek gagal atau investasi pemerintah yang rugi bukan berarti korupsi, karena ada faktor eksternal seperti pasar, inflasi, atau bencana.
Bayangkan jika setiap kerugian di sektor publik otomatis dianggap korupsi — tak ada pejabat yang berani mengambil risiko kebijakan baru.
4. ⚖️ Pemisahan Ranah Hukum dan Manajemen
Negara maju memisahkan ranah hukum pidana, administratif, dan kebijakan publik secara tegas.
Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dengan motif pribadi.
Sementara kesalahan manajerial adalah pelanggaran prosedur, bukan kejahatan.
Di Indonesia, batas ini sering kabur. Banyak pejabat daerah akhirnya dipidana karena perbedaan tafsir kebijakan atau audit keuangan, bukan karena mencuri uang.
📚 Kasus Nyata: Ketika “Kerugian Negara” Disalahpahami
Contoh klasik: seorang kepala daerah mengeluarkan dana hibah untuk mendukung event pariwisata. Setelah audit, BPK menemukan prosedur yang tidak sesuai aturan, lalu disebut “menyebabkan kerugian negara Rp300 juta”.
Padahal, dana itu benar-benar digunakan untuk acara, tidak ada yang diselewengkan.
Tapi karena angka kerugian tercatat, pejabat tersebut terancam pidana korupsi.
Di negara maju, kasus seperti ini hanya berujung pada sanksi administratif atau evaluasi prosedur, bukan penjara.
🧠 Mengapa Indonesia Berbeda?
Perbedaan ini tak lepas dari sejarah hukum kolonial dan reformasi anti-korupsi di Indonesia.
Setelah krisis 1998, publik mendesak penegakan hukum keras terhadap korupsi. Maka disusunlah UU Tipikor yang kuat — bahkan lebih kuat dari banyak negara lain.
Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum menjadi terlalu luas, menjerat banyak kasus non-korupsi.
Akibatnya, muncul “efek takut” di kalangan birokrat: mereka lebih memilih diam daripada membuat kebijakan yang berisiko.
Padahal, pemerintahan yang sehat butuh inovasi dan keberanian mengambil keputusan.
🌍 Refleksi: Belajar dari Negara Lain
Negara maju menempatkan korupsi sebagai kejahatan moral dan etika kekuasaan, bukan semata angka di laporan keuangan.
Mereka memandang kerugian negara sebagai hal yang bisa diperbaiki secara administrasi, selama tidak ada niat jahat.
Pendekatan ini menciptakan keseimbangan:
- Pejabat yang jujur tapi salah kebijakan tidak dipenjara,
- Tapi mereka yang curang dan memperkaya diri tetap dihukum berat.
Sementara di Indonesia, garis pembeda ini belum tegas.
Konsep “kerugian negara” sering dijadikan pintu masuk hukum pidana, bahkan sebelum ada bukti motif koruptif.
🏁 Penutup: Saatnya Reformasi Konsep Korupsi
Indonesia butuh pendekatan baru dalam memaknai korupsi.
Bukan berarti kita melemahkan penegakan hukum, tapi justru memperkuat akurasi dan keadilan.
Korupsi sejati adalah ketika kekuasaan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
Sementara kesalahan administratif, kebijakan gagal, atau kerugian anggaran yang tidak disertai niat jahat seharusnya diselesaikan di ranah tata kelola, bukan pidana.
Negara maju telah membuktikan: sistem hukum yang adil bukan yang paling keras, tapi yang paling tepat sasaran.
Dan mungkin, sudah saatnya Indonesia mulai meninjau ulang paradigma lama itu — agar hukum tak hanya menghukum, tapi juga memberi ruang belajar dan memperbaiki diri.